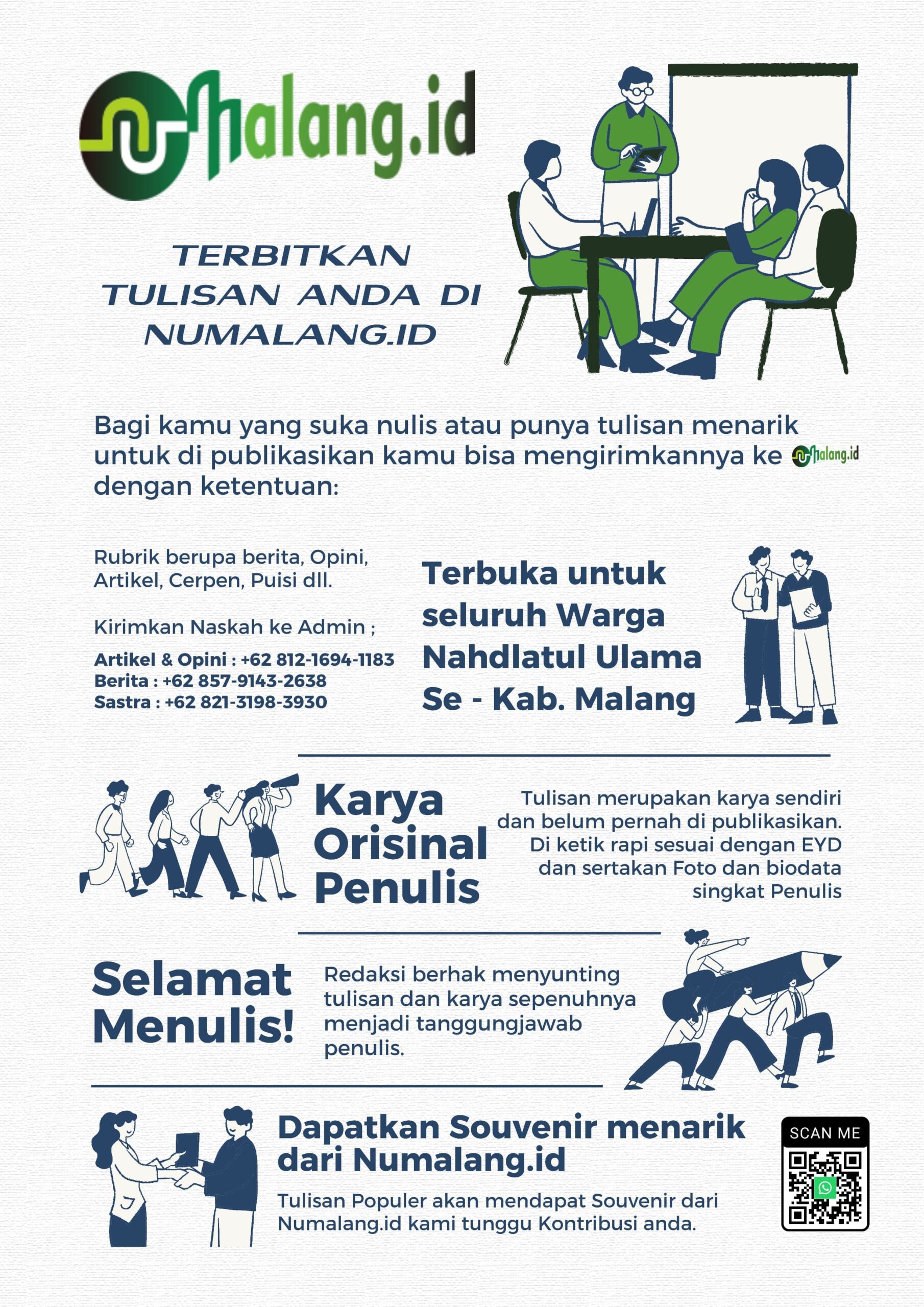Ketika Hari Santri diperingati, santri dipertarungkan. Ketika negara mengabadikan santri dalam kalender nasional, sebagian publik justru mengadilinya di layar gawai. Esai ini mencoba membaca ulang pertarungan narasi itu—bukan untuk membela, bukan untuk menggugat, tetapi untuk membedahnya.
Hari-hari ini, kata “santri” terasa seperti tubuh yang diletakkan di meja operasi opini publik. Pisau komentar bergerak tanpa anestesi, tangan-tangan yang mungkin tak pernah merasakan bangku ngaji menyayat tanpa ragu. Di saat negeri akan merayakan Hari Santri dengan baliho, pidato, dan seremoni di bulan ‘Santri’ ini, ruang media sosial sudah lebih dulu berubah menjadi ruang sidang: santri dianggap budak, pesantren disebut feodal, kiai dituduh raja.
Ironi itu tidak kecil: yang diperingati negara, sedang dihina publik; yang diselamatkan dalam sejarah, sedang diadili dalam trending topic.
Tapi mari kita jujur, tidak semua orang menuduh karena benci. Ada yang bicara karena pernah terluka. Ada yang bicara karena pengalaman yang belum selesai. Ada yang bicara hanya dari cerita orang lain yang belum tentu benar. Banyak pula, dan ini problem kita, yang berbicara hanya dari tangkapan layar dan potongan narasi, lalu memukul rata, seolah seluruh dunia pesantren sama. Padahal realitasnya jauh lebih rumit daripada yang bisa diringkas dalam satu postingan pendek.
Di sisi lain, ada juga pembelaan yang lahir dari refleks keagamaan yang kurang mau mendengar. Kritik cepat dianggap makar, setiap luka dianggap sekadar ujian, dan setiap suara perbedaan dinilai sebagai durhaka. Slogan “santri bukan budak” terus digaungkan, sementara sebagian praktik patronase, kultus figur, dan relasi kuasa tetap berlangsung tanpa ruang evaluasi.
Keduanya, yang menghujat gegabah dan yang membela tanpa berpikir — sesungguhnya anak dari rahim yang sama: kita semua malas membaca realitas dengan kedalaman. Kita lebih mudah menuduh daripada memahami; lebih cepat menolak daripada membedah; dan lebih suka romantika ketimbang otopsi cara pandang.
Dan tepat di bulan ketika “santri” diagungkan di panggung negara, kata itu dipakai publik untuk menguliti sesuatu yang jauh lebih tua dari isu yang sedang viral: hubungan antara ilmu, otoritas, dan tubuh manusia di ruang bernama pesantren. Karena masalah ini, sejatinya, bukan tentang marah atau tidak marah, bangga atau tidak bangga — ini tentang bagaimana kita membaca.
Itu sebabnya, artikel ini tidak akan membela, tidak pula mengganyang. Yang akan dilakukan hanyalah satu: membuka badan wacana ini seperti ahli forensik membuka jenazah — bukan untuk memutuskan siapa yang salah, melainkan untuk melihat apa yang sebenarnya sedang bekerja di balik tuduhan, kemarahan, pembelaan, dan mitos.
Ini bukan pledoi. Bukan pula dakwaan. Ini seperti judulnya, sebuah otopsi cara pandang.
Tentang “Feodalisme” dan Hakikat Taat: Pandangan Santri yang Tidak Sanggup Menutup Mata
Saya santri. Dan saya paham mengapa sebagian orang di luar sana alergi pada kata “taat”. Mereka mencium aroma feodal dalam cara santri berdiri, cara kami duduk di hadapan kiai, cara kami menerima perintah tanpa rapat argumentatif. Bagi mereka, ini problem mental, bukan etika.
Tapi begini, taat di pesantren tidak lahir dari rasa takut. Ia lahir dari ilmu. Dan ilmu lahir dari trust — kepercayaan yang diuji oleh usia, kemanfaatan, dan keberlangsungan.
Kalau hubungan kami dengan kiai hendak disebut feodal, maka feodalisme macam apa yang membuat murid-muridnya justru menjadi orang yang berdiri sendiri, membuka pesantren baru, menelurkan buku, memimpin lembaga, mendidik ribuan orang — tanpa sekali pun diminta menyembah manusia?
Yang feodal itu yang meminta sujud pada kekuasaan. Pesantren tidak pernah meminta sujud kepada kiai — ia meminta sujud kepada disiplin.
Memang ada oknum. Ada pesantren yang mengelola kuasa tanpa mekanisme koreksi. Tetapi menjadikan anomali sebagai definisi adalah kemalasan intelektual. Sama saja seperti menyimpulkan seluruh dokter itu korup hanya karena ada satu kasus jual beli surat sakit.
Taat di pesantren bukan kemandulan berpikir.
Taat adalah fondasi agar pikiran tidak liar sebelum waktunya matang.
Dan di titik ini saya ingin berkata lantang: para santri bukan generasi yang gagap terhadap kritik. Kami hanya tidak sudi tunduk pada narasi yang ingin memukul warisan ulama dengan teori-teori yang bahkan belum sempat dilahirkan ketika pesantren telah ratusan tahun beroperasi sebagai universitas tanpa gedung.
Bila ada yang ingin mengoreksi pesantren, kritiklah dengan ilmu — bukan dengan sinis. Kami santri akan mendengar, bukan karena kami inferior, tetapi karena kami terbiasa tumbuh dengan ilmu yang tidak pernah selesai diperbaiki.
Isu eksploitasi santri, feodalisme kiai, dan tuduhan bahwa pesantren melahirkan mental tunduk biasanya tumbuh dari cara baca yang mengimpor kategori industri atau politik ke dalam tradisi agama. Jika seluruh relasi kerja dibaca memakai rumus upah, maka khidmah memang akan tampak sebagai perbudakan. Jika seluruh hirarki dibaca sebagai dominasi, maka disiplin akan tampak sebagai represi, dan penghormatan akan tampak sebagai kultus figur. Pada titik ini, masalah tidak terletak pada apa yang terjadi di pesantren, tetapi pada lensa yang dipakai untuk menilai.
Keterlibatan santri dalam pembangunan pesantren sering disalahartikan sebagai tenaga gratis. Padahal hubungan yang terjadi bukan hubungan jual-beli tenaga, tapi hubungan timbal balik yang berbasis nilai: ada akses ilmu, tempat tinggal, bimbingan pikiran, dukungan sosial, dan legitimasi keilmuan. Memaksa tradisi yang berjalan dengan logika makna untuk tunduk pada logika upah adalah cara baca yang mengabaikan realitas tradisi itu sendiri.
Relasi kiai–santri pun sering disalahpahami karena hirarki dianggap identik dengan penindasan. Dalam tradisi ilmu, otoritas bukan ancaman, melainkan alat kurasi. Tidak semua suara memiliki derajat bobot yang sama terhadap kebenaran. Menyamakan seluruh opini dengan dalih anti-feodal justru menimbulkan kezaliman intelektual yang tak kalah berbahaya dibanding ketaatan buta.
Konsep barokah dan khidmah juga kerap dikritik sebagai cara membius mental santri. Padahal bagi ekologi pesantren, barokah bukan alasan untuk berhenti bekerja, tapi sumber makna yang membuat lelah tidak berubah jadi putus asa. Menilai tradisi pesantren setelah menyingkirkan aspek metafisiknya sama saja seperti menilai kekokohan bangunan setelah fondasinya sengaja dirobohkan dulu.
Penyimpangan itu memang ada, dan ruang koreksi harus tetap terbuka. Tapi menjadikan penyimpangan sebagai gambaran umum adalah cara baca yang salah. Satu kasus tidak bisa menggantikan konsep. Menghakimi seluruh pesantren hanya karena segelintir pelanggaran dari oknum adalah tindakan yang mungkin terasa mudah, tapi itu tidak dibenarkan.
Pada akhirnya, pembacaan yang tergesa terhadap pesantren lebih menunjukkan keterbatasan kategori penilai daripada cacat inheren pada tradisi itu sendiri. Bukan setiap struktur tertutup adalah tirani; kadang ia adalah pagar bagi sesuatu yang tidak boleh bocor. Dan sering kali yang tampak seperti kegelapan bukan berasal dari ruang yang diamati — melainkan dari rendahnya intensitas lampu yang dipakai untuk melihat.
Dan di tengah gegap-gempita tuduhan feodalisme itu, sejarah diam-diam bergerak ke arah lain: apa yang pernah diprediksi Nurcholish Madjid (Cak Nur) —yang diulas oleh Prof. Nadirsyah Hosen pada laman sosial medianya— kini menjadi fakta. Gelombang santri justru menembus laboratorium, universitas, dan forum akademik dunia.
Mereka mengajar filsafat di Amerika, menulis teori feminisme di Chicago, meneliti biostatistik di Belgia, menjadi profesor teknik di Jepang, memimpin riset industri di Jerman, hingga memegang jabatan strategis negara di dalam negeri. Santri, yang katanya hidup dalam kultur taat, justru tampil sebagai produsen ilmu, bukan objek kuasa. Mereka menulis jurnal ilmiah sambil tetap membaca Ihya’, mengajar epistemologi sambil tetap bershalawat, dan melampaui batas ruang yang dulu dikira memenjarakan mereka.
Gelombang baru ini memperlihatkan satu hal: pesantren bukan pabrik budak, tetapi inkubator mobilitas intelektual. Apa yang tampak sebagai kepatuhan di awal, ternyata justru menjadi mesin lahirnya generasi yang mampu berjalan jauh — bahkan keluar dari orbit asalnya — tanpa kehilangan gravitasi rohaninya.
Maka jika hari ini ada yang ingin mengadili pesantren, silakan. Kritik adalah bagian dari peradaban. Tapi janganlah menilai tradisi tua dengan logika yang baru kemarin ditemukan, apalagi dengan kebencian yang lahir dari serpihan cerita. Santri bukan malaikat, pesantren bukan sorga, dan kiai pun manusia. Ada salah, ada luka, ada ruang koreksi — tetapi ada pula capaian, warisan, dan lompatan sejarah yang tak bisa disapu bersih hanya karena satu-dua potret buruk viral di layar ponsel.
Pada akhirnya, Hari Santri bukan hanya peringatan atas masa lalu yang pernah berjasa, tetapi ujian atas masa depan yang masih harus diperjuangkan. Santri yang setia pada tradisinya tidak sedang berjalan mundur — ia sedang memastikan dirinya punya akar saat melangkah. Dan santri yang mau dikritik, diperiksa, dan dievaluasi, justru sedang menyalakan kemungkinan baru. Barangkali di situlah letak tugas kita hari ini: tidak membuktikan bahwa santri tak bersalah — tetapi menunjukkan bahwa santri pantas dipercaya untuk ikut menghidupi masa depan republik ini.
Selamat Hari Santri.
Yang diperingati negara tidak sedang punah; ia justru sedang tumbuh.
Penulis: Zakiya Maajid