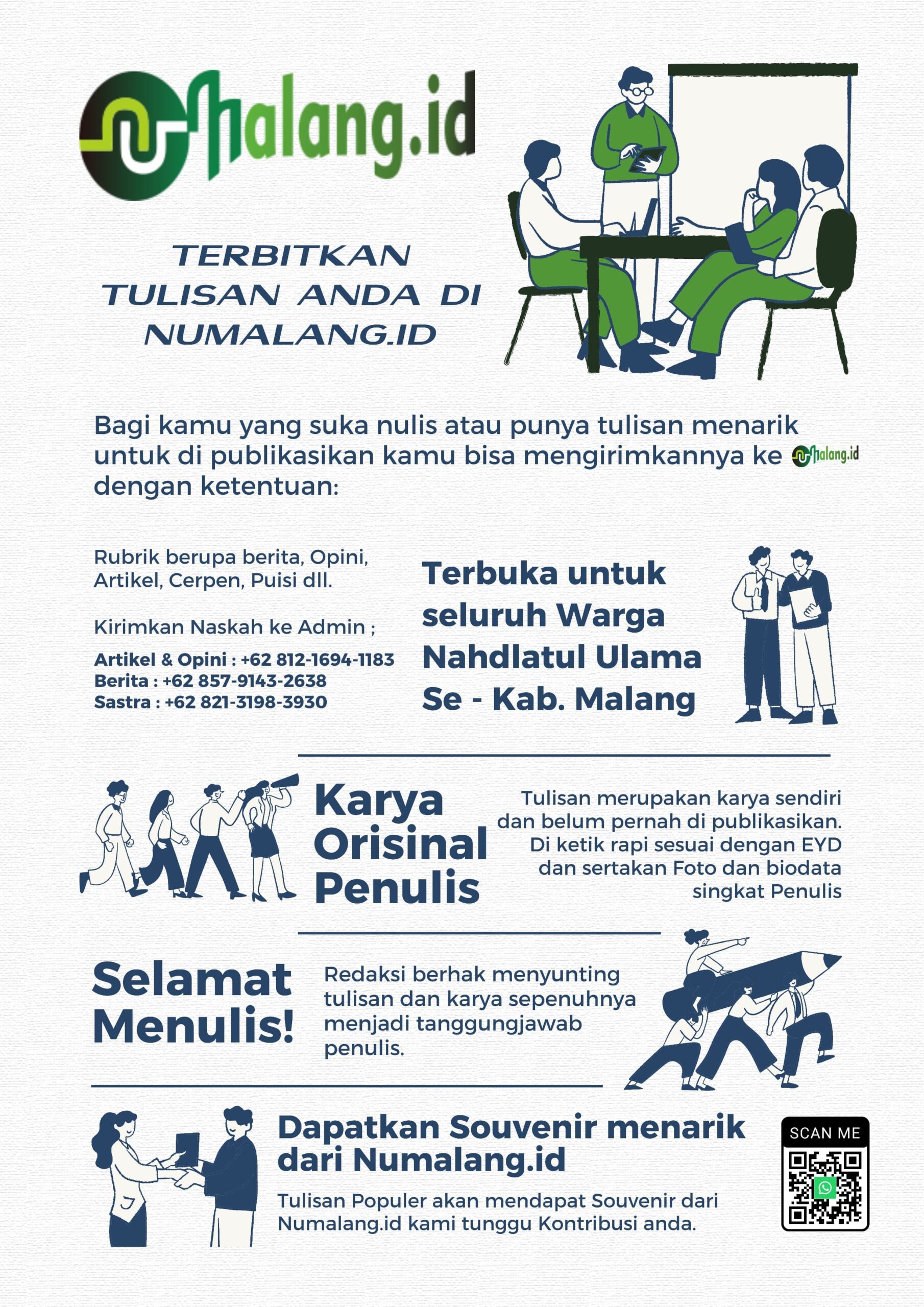NUMALANG.ID-Belakangan ini publik diguncang oleh insiden penyerangan terhadap seorang vokalis band hardcore saat ia tampil di tengah kerumunan. Panggung yang seharusnya menjadi ruang untuk bersenang-senang seketika berubah menjadi tragedi yang tak perlu. Di balik hiruk-pikuk musik keras itu, praktik moshing kembali menonjol—ritual khas skena hardcore yang dipenuhi aksi saling dorong, menendang, menjatuhkan badan, hingga berlari menabrakkan diri ke sesama penonton. Bagi sebagian orang, itu dianggap bagian dari budaya musik keras; namun bagi banyak lainnya, muncul satu pertanyaan krusial: Mengapa begitu banyak remaja rela mempertaruhkan keselamatan hanya untuk ledakan adrenalin yang berlangsung sekejap?
Dalam budaya populer, moshing sering dipandang lumrah. Banyak yang menyebutnya sebagai cara melepas energi dan mengekspresikan diri secara total. Namun ketika tindakan ekstrem tersebut mulai menyebabkan cedera serius hingga kehilangan nyawa, kita perlu meninjaunya lebih kritis. Fenomena ini bukan sekadar gaya bermusik, tetapi cermin dari persoalan pendidikan emosional, moral, dan sosial yang belum tertangani secara tuntas.
Penelitian Cornell University (Silverberg, 2013) menggambarkan mosh pit sebagai ruang dengan gerakan menyerupai sistem kacau, di mana arah gerak tubuh tidak dapat diprediksi. Akibatnya, potensi cedera tidak hanya tinggi, tetapi hampir pasti terjadi. Meski demikian, risiko tersebut justru dipandang sebagai bagian dari sensasi. Banyak remaja merasa moshing memberi rasa kebersamaan dan keberanian, meskipun tubuh mereka menjadi taruhannya. Hal ini menunjukkan bagaimana kesadaran logis sering kali tergusur oleh dorongan emosional, pencarian identitas, dan tekanan kelompok.
Urgensi Pendidikan Emosional bagi Remaja
Fenomena moshing memperlihatkan bahwa remaja membutuhkan pendidikan emosional yang lebih kuat. Daniel Goleman (1995) menegaskan bahwa kecerdasan emosional meliputi kemampuan mengenali emosi diri, mengolahnya secara sehat, serta mengekspresikannya dengan cara yang tidak merugikan. Ketika pendidikan hanya menekankan ranah akademik, sementara pembinaan emosi kurang mendapat perhatian, remaja cenderung mencari bentuk ekspresi lain yang sayangnya tidak selalu aman.
Selain itu, tekanan sosial dalam kelompok musik hardcore turut memperkuat keterlibatan remaja dalam moshing. Sebagian merasa bahwa menolak ikut serta sama saja dengan kehilangan solidaritas. Di sinilah pendidikan keluarga dan sekolah berperan penting. Keduanya harus mampu membangun kepercayaan diri remaja agar mereka tidak mudah terbawa arus. Keluarga sebagai ruang pertama tumbuh kembang perlu memberikan pendampingan emosional, pengawasan yang proporsional, dan dialog terbuka tentang pilihan hobi serta risiko yang mengikutinya.
Sekolah melalui Kurikulum Merdeka sebenarnya telah memasukkan Pembelajaran Sosial Emosional sebagai elemen penting. Namun implementasinya sering terkendala oleh beban kurikulum atau kurangnya pemahaman pendidik. Padahal, penguatan regulasi emosi, empati, dan kesadaran risiko jauh lebih penting dari sekadar menghafal materi pelajaran. Remaja harus dibiasakan berpikir reflektif sebelum bertindak, memahami batas aman, serta melihat diri sendiri bukan hanya sebagai individu bebas, tetapi sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab sosial.
Fenomena moshing juga menyingkap lemahnya internalisasi pendidikan moral dan agama. Ajakan untuk menjaga keselamatan jiwa (hifz an-nafs) sering kali berhenti pada teori. Ketika nilai itu tidak dihidupkan dalam perilaku sehari-hari, remaja sulit menghubungkannya dengan pilihan tindakan mereka, termasuk saat berada di lingkungan konser. Padahal, ajaran moral bertujuan membimbing manusia agar mampu membedakan antara ekspresi yang membangun dan tindakan yang merusak.
Selain pendidikan, komunitas musik pun memiliki tanggung jawab moral. Penyelenggara konser dapat mengatur mosh pit dengan pengawasan ketat, memberikan edukasi keselamatan sebelum acara, atau bahkan menolak praktik moshing jika terbukti membahayakan. Musik tidak seharusnya menjadi ruang kekerasan yang disamarkan sebagai hiburan. Energi musik keras bisa tetap dinikmati tanpa harus membuat penontonnya terluka.
Pada akhirnya, fenomena moshing mengingatkan kita bahwa ekspresi tidak boleh mengorbankan keselamatan. Remaja perlu dididik bahwa keberanian sejati bukanlah tubuh yang dibenturkan di kerumunan, melainkan kemampuan menjaga diri, mengendalikan emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Musik boleh keras, tetapi kesadaran harus tetap menjadi pemimpinnya. Sebelum kaki melompat ke kerumunan, sebelum tubuh terdorong ke tengah mosh pit, marilah mengajarkan kepada generasi muda bahwa keselamatan adalah bagian dari martabat manusia.
Pendidikan emosional bukan pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak. Tanpa itu, remaja akan terus mencari ruang pelampiasan tanpa batas. Tetapi dengan pendidikan yang tepat, mereka dapat mengekspresikan diri secara kreatif, energik, namun tetap menghargai kehidupan. Dan itulah tugas kita: memastikan bahwa setiap ekspresi anak bangsa tidak justru membawa mereka pada bahaya, melainkan pada kedewasaan.
Oleh: Khusnul Fatimah, M.Pd.
Guru Bahasa Indonesia MTs Hasyim Asy’ari Kota Batu dan Pengurus PC Fatayat NU Kota Batu
Editor: Moh. Ahsan Shohifur Rizal
Daftar Rujukan
Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. Bantam Books.
Silverberg, J. L. et al. (2013). Collective Motion of Humans in Mosh and Circle Pits. Physical Review Letters.