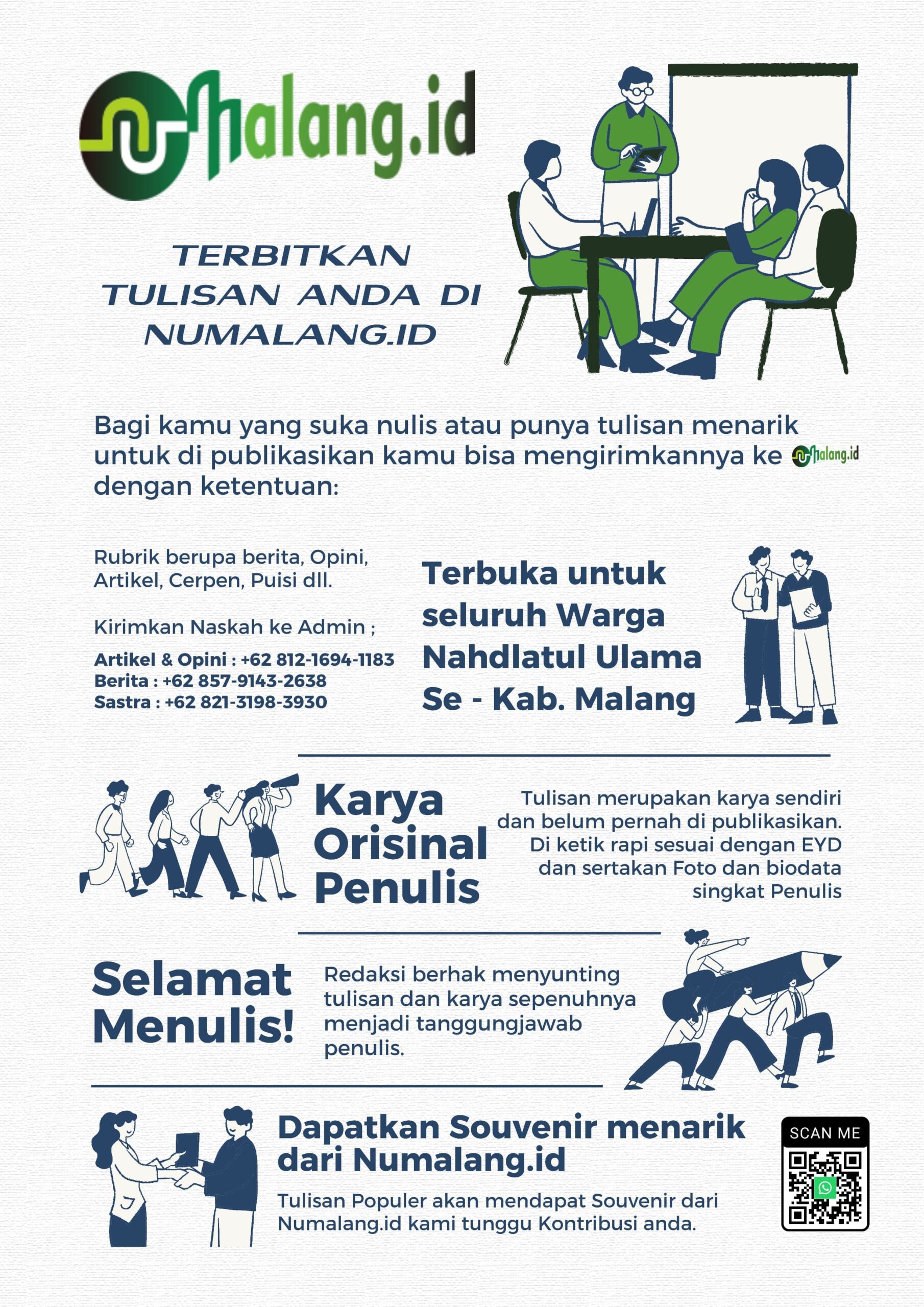numalang.id — Masihkah sastra punya tempat di tengah dunia yang serba cepat, digital, dan pragmatis?
Pertanyaan itu kerap menghantui setiap kali mataku menatap wajah-wajah muda di ruang kelas wajah yang lebih akrab dengan cahaya gawai ketimbang aroma buku. Aku seorang guru Akidah Akhlak, pecinta literasi, sekaligus penyandang disabilitas. Setiap hari aku bergulat dengan dua tantangan besar: keterbatasan tubuh dan derasnya arus zaman yang kian menelan nilai-nilai luhur yang dulu begitu dijaga.
Sebagai guru, aku harus menyesuaikan diri dengan tuntutan modernitas. Namun sebagai pencinta sastra, aku tak ingin kehilangan ruh kemanusiaan yang dikandungnya. Di antara keduanya, aku berdiri di simpang jalan: bagaimana mendidik agar murid tetap relevan dengan zaman, tanpa kehilangan kedalaman rasa dan makna hidup yang justru menjadi inti dari sastra?
Sastra dan Arus Zaman yang Bergegas
Bagi sebagian murid masa kini, sastra adalah sesuatu yang usang. Mereka lebih akrab dengan teks di media sosial ketimbang paragraf panjang dalam cerpen klasik; lebih hafal kutipan motivator dunia maya daripada bait puisi Gus Mus. Aku tak bisa menyalahkan mereka, sebab dunia mereka memang berbeda dari masa mudaku. Namun di situlah letak pergulatannya: bagaimana membuat sastra tetap hidup di hati generasi yang tumbuh dalam budaya instan?
Sebagai guru disabilitas, aku terbiasa menghadapi keterbatasan. Namun menghadapi minimnya minat terhadap sastra adalah perjuangan lain yang jauh lebih sunyi. Sebab sesungguhnya, sastra bukan sekadar pelajaran tentang teks ia adalah pelajaran tentang kehidupan. Ia mengajarkan cara merasa, memahami, dan menjadi manusia. Di tengah arus zaman yang memuja kecepatan, sastra hadir sebagai penyeimbang, mengajak kita melambat dan merenung.
Dilema Mendidik di Tengah Perubahan Nilai
Zaman ini memuja segala yang cepat: belajar cepat, sukses cepat, bahkan mencinta pun cepat. Paradigma ini menyelinap ke ruang kelas murid ingin jawaban instan tanpa melewati proses berpikir panjang. Mereka lebih terobsesi pada hasil ketimbang makna. Namun aku percaya, pendidikan sejati bukan tentang “seberapa cepat”, melainkan “seberapa dalam” seseorang memahami dirinya dan dunia.
Sastra menolak kecepatan seperti itu. Ia menuntut jeda, menuntun pembacanya merenung dan merasakan makna di balik kata. Tetapi dalam sistem pendidikan modern yang berorientasi pada hasil, sastra kerap dianggap tidak produktif. Maka aku bertanya pada diri sendiri: apakah harus ikut arus agar relevan, atau tetap bertahan agar bermakna?
Sebagai guru disabilitas, aku belajar bahwa hidup adalah keseimbangan antara kemampuan dan harapan. Maka dalam mengajar, aku mencari jalan tengah menghadirkan sastra dengan wajah yang akrab bagi generasi digital. Kadang aku meminta murid membuat puisi dalam bentuk video pendek, atau menulis kisah para nabi dengan gaya naratif masa kini. Dari situ aku belajar: sastra tak pernah hilang, hanya berganti rupa. Barangkali Chairil Anwar tak lagi menulis di kertas, namun semangatnya tetap hidup di antara “caption” jujur yang menggugah di layar ponsel. Bukankah itu juga bentuk baru dari sastra?
Empati, Ruh Pendidikan yang Terlupakan
Sebagai penyandang disabilitas, aku tahu bagaimana rasanya dipandang berbeda, diremehkan, bahkan dihakimi. Tapi pengalaman itu justru mengajariku satu hal: setiap manusia punya cerita yang patut dipahami sebelum dinilai. Dan sastra adalah ruang paling indah untuk menumbuhkan empati itu.
Ketika murid membaca kisah orang miskin, penyandang disabilitas, atau tokoh yang terpinggirkan, sejatinya mereka sedang belajar menjadi manusia yang lebih peka. Di tengah dunia yang dingin oleh teknologi, sastra menjadi pemanas jiwa. Ia mengajarkan untuk memahami, bukan sekadar berkomentar; menumbuhkan rasa, bukan sekadar menambah data.
Namun, menumbuhkan empati bukan hal mudah. Di sinilah peran guru diuji menjadi jembatan antara nilai kemanusiaan sastra dan logika dunia digital.
Antara Kurikulum dan Nurani
Sebagai guru, aku terikat oleh kurikulum. Tapi sebagai manusia, aku terikat oleh nurani. Tak jarang keduanya bertabrakan: kurikulum mengejar nilai, sedangkan hatiku ingin menanamkan kesadaran. Kurikulum menuntut target, sedangkan sastra meminta waktu untuk merenung.
Aku pernah merasa lelah mengejar angka kompetensi dasar hingga lupa bahwa di hadapanku bukan sekadar siswa, melainkan jiwa-jiwa yang tengah mencari arah. Aku pernah nyaris menyerah, menyaksikan adab siswa memudar di tengah realita rumah dan gawai.
Namun, dari keterbatasanku aku belajar: mengajar bukan soal seberapa cepat bergerak, melainkan seberapa dalam memberi makna. Begitulah sastra bekerja bukan dalam laju, tapi dalam kedalaman.
Sastra Sebagai Rumah Makna
Masalah terbesar pendidikan modern bukan pada teknologi, melainkan pada hilangnya keseimbangan antara akal dan rasa. Kita sibuk mencetak siswa yang cerdas, tapi lupa menumbuhkan manusia yang berperasaan. Kita mengajarkan literasi digital, tapi melupakan literasi hati.
Sastra hadir untuk menjembatani dua dunia itu. Ia menjadi ruang pertemuan antara pikiran dan perasaan, logika dan kepekaan. Melalui cerita rakyat, siswa belajar berpikir kritis dan kolaboratif. Melalui puisi, mereka belajar mengekspresikan empati. Melalui drama digital, mereka belajar berkomunikasi lintas nilai.
Dengan pendekatan ini, sastra tidak lagi dianggap kuno. Ia justru menjadi jiwa dari pendidikan modern yang manusiawi. Guru disabilitas seperti aku pun mendapat ruang: tak perlu bersaing dalam kecepatan, cukup unggul dalam kepekaan dua hal yang justru paling dibutuhkan di era ini.
Mengajar dengan Hati
Zaman boleh berubah, teknologi boleh melesat, tapi manusia tetaplah makhluk pencari makna. Dan sastra, dengan segala kesederhanaannya, akan selalu menjadi rumah bagi pencarian itu.
Sebagai guru disabilitas, aku belajar bahwa mendidik bukan soal menyamakan langkah, tapi menemukan ritme bersama antara guru dan murid, masa lalu dan masa kini, logika dan rasa.
Dilema mendidik di tengah zaman yang bergerak cepat bukan untuk dihindari, melainkan dipahami. Sebab setiap zaman membawa bahasanya sendiri, dan tugas guru adalah menemukan bahasa yang mampu menyentuh hati murid di zamannya.
Dan jika ada yang bertanya,
“Mengapa masih bertahan dengan sastra di era digital ini?”
Aku akan menjawab:
“Karena hanya lewat sastra, aku bisa mengajar dengan hati meski langkahku tertatih, kata-kataku akan terus berjalan jauh.” (*)
Kontributor: Ali Rofik (MTs Ash Sholihuddin – Dampit)