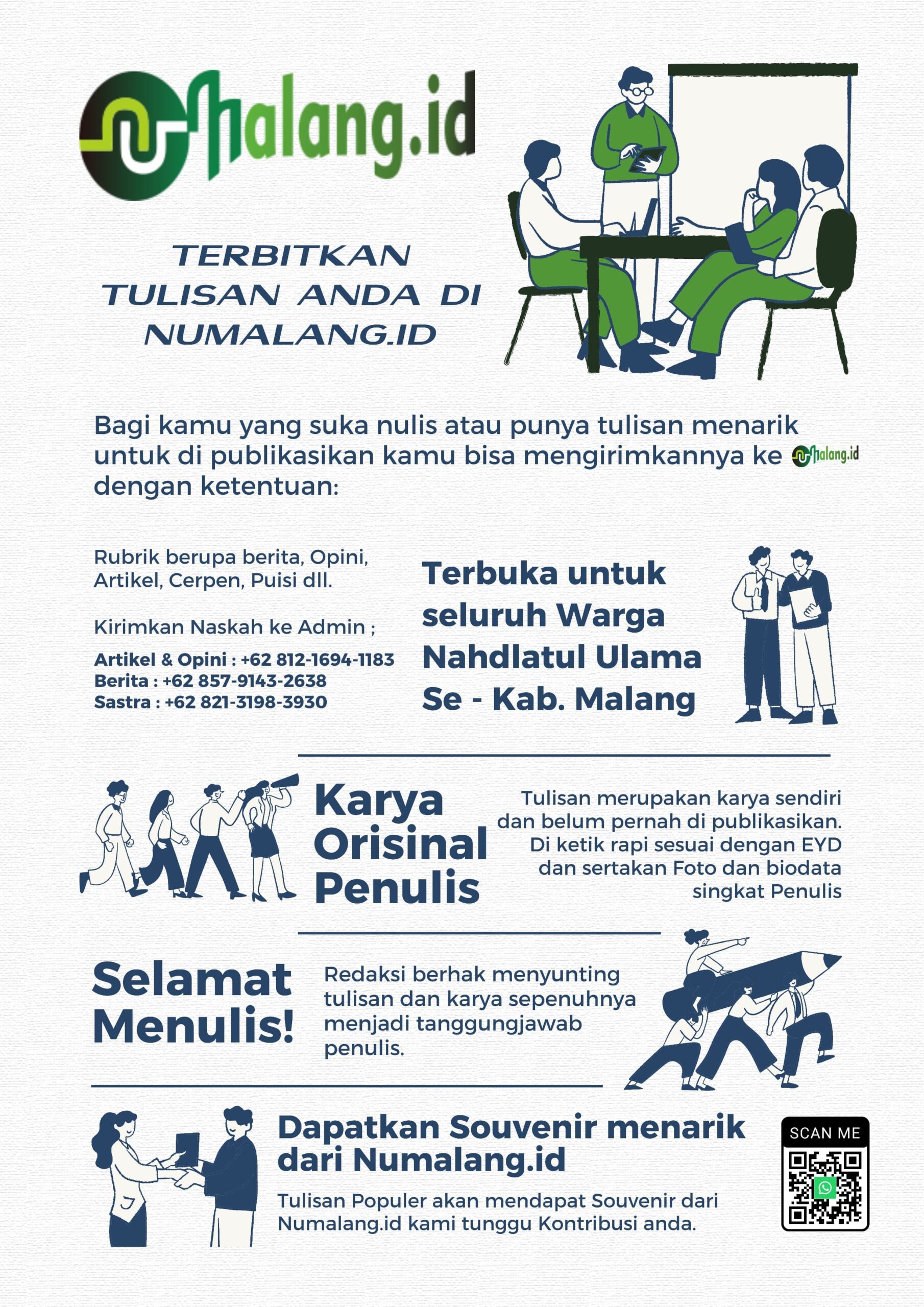NUMALANG.ID.Malang., Bagian II Ngapit Lacak Jejak Ulama Lor Asal Persia Eyang Segalor
Tepatnya pada Jum’at: 5 September 2025. Jam; 21:13 Wib. Bertempat di rumah bapak H. Eko Hadi Santoso di dusun Kauman desa Kaumrejo kecamatan Ngantang kabupaten Malang, kami transit dan sekaligus silaturrahmi karena beliau juga pengurus LESBUMI Ngantang. Sebelum memulai Ngapit Lacak Jejak, kami LESBUMI PCNU kabupaten Malang, LESBUMI Ngantang dan LESBUMI Lawang, memastikan kembali rute mana dulu yang akan kami tempuh. Dan malam itu di sepakati sampai pada jam; 04:00 Wib, karena tidak semua jalur tempuh yang akan kita lalui tersebut kami up secara langsung ke media daring online.
Beberapa titik Ngapit Lacak Jejak kita konfirmasikan ke media daring karena memang titik “cagar budaya” tersebut baik yang ada dalam campur tangan pemerintah ataupun mandiri atas kepedulian masyarakat sekitar, memang dalam kapaistas skala Nasional. Agaenda kegiatan ini adalah dalam rangka memperingati Maulidurrosul Nabi Muhammad Saw 1447 H. Di samping itu misi penting dan misi suci dari Ngapit Lacak Jejak ini adalah masyarakat setempat yang bersentuhan langsung dengan area “cagar budaya” akan semakin peduli, akan semakin perhatian dalam merawat serta menjaga titik cagar budaya yang ada di tempat mereka.
Selain itu Ngapit Lacak Jejak ini adalah bagian integral dari “strategi Saptawikrama” yakni tujuh strategi kebudayaan Islam Nusantara atau dalam bahasa pesantrennya “al-Qowaid as-Sab’ah”, adapun hasil rapat kerja nasional LESBUMI PBNU pada awal tahun 2016, di gedung PBNU Jln. Kramat Raya no. 164. Jakarta, yang tertuang dalam tujuh butir strategi Saptawikrama tersebut adalah;
- Menghimpun dan mengonsolidasi gerakan yang berbasis adat istiadat, tradisi dan buadaya Nusantara
- Mengembangkan model pendidikan sufistik “tarbiyah wa ta’lim” yang berkaitan erat dengan realitas di tiap satuan pendidikan terutama yang di kelola lembaga pendidikan formal “Maarif dan rabithah ma’had islamiyah “RMI”
- Membangun wacana independen dalam memaknai kearifan lokal dan budaya Islam Nusantara secara ontologis dan epistimologis keilmuan
- Menggalang kekuatan bersama sebagai anak bangsa yang bercirikan bhenika tunggal ika untuk merajut kembali peradaban maritim nusantara
- Menghidupkan kembali seni budaya yang beragam dalam ranah bhenika tunggal ika berdasarkan nilai kerukunan, kedaimaian, toleransi, empati, gotong royong dan keunggulan dalam seni budaya dan ilmu pengetahuan
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan gerakan Islam Nusantara
- Mengutamakan prinsip juang berdikari sebagai identitas bangsa untuk menghadapi tantangan global
Pada hari Kamis, 3 Juli 2025. Jam; 04:09 Wib. Di Jalan Durian No.20, Prabon II, dusun Kauman desa Kaumrejo, Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, Jawa Timur 65392. Tepatnya di barat masjid Besar Baiturrohman, kami sowan ke makbaroh Syaikh Abdul Adhim bin Baidhowi atau “Eyang Segalor”. Sebagai ciri khas santri dan penjagaan terhadap tradisi masyarakat Ashlussunnah wal-Jamaah ala Nahdlotil Ulama, kami memulainya dengan tawasulan kemudian pembacaan tahlil dan umbul dungo yang kami hadiahkan kepada beliau Syaikh Abdul Adhim bin Baidhowi atau masyarakat setempat populer menyebutnya “Eyang Segalor”.
Di dalam buku Atlas Wali Songo, Kyai Ngabei H. Agus Sunyoto menguraikan. Sebagian orang menafsirkan guru Sri Mapanji Jayabhaya adalah Mpu Sedah, sementara sebagian lainnya menafsirkan bahwa Mpu Sedah adalah guru Sri Mapanji Jayabhaya di bidang sastra, sedangkang sang bhiksu pandhita adhikara yang disebut dalam Hariwangsa adalah Syaikh Samsuddin al-Wasil yang tidak sekedar mengajarkan “ilmu perbintangan dan nujum”, melainkan pula “karomah-karomahnya” yang digambarkan seperti kesaktian Rsi Agastya. Sebutan bhiksu dan kemudian pandhita, lazim digunakan untuk menyebut tokoh-tokoh pemuka Islam pada zaman itu, seperti area makam Fatimah binti Maimun yang dalam “prasasti Leran” disebut susuk “tempat suci”, sebutan pandhita untuk Syaikh Maulana Malik Ibrahim, pengangkatan saudara tua Raden Rahmat yang bernama Ali Murtadho sebagai Raja Pandhaita di Gersik, sebutan Pandhita Ampel untuk Sunan Ampel, Pandhita Giri untuk Sunan Giri dan keturunannya. Lepas dari sulitnya merekontruksi sejarah Syeikh Syamsuddin al-Wasil dari kajian arkeologis, catatan historiografi dan cerita tutur masyarakat muslim Jawa, meyakini bahwa almarhum yang dikebumikan di kompleks makam Setana Gedong adalah seorang tokoh sufi yang sakti asal negeri Rum “Persia” yang di yakini menjadi guru rohani Sri Mapanji Jayabhaya raja Kediri. Lantaran itu situs makam kuno yang terletak di dekat reruntuhan Candi Kuno di kompleks pemakaman Setana Gedong kota Jediri itu, sampai kini masih di jadikan pusat ziarah dan dikeramatkan oleh masyarakat.
Makam tokoh Persi lainnya yang sezaman dengan kisah legenda kedatangan orang-orang Lor asal Persia adalah makam “Eyang Segalor” yang terletak di depan masjid desa Sumberagung kecamatan Ngantang kabupaten Malang yang diyakini masyarakat sebagai makam yang sudah ada pada masa jauh sebelum Wali Sanga. Makam tua yang di hubungkan dengan Sri Mapanji Jayabhaya ini, kiranya di hubungkan dengan prasasti Hantang yang memaklumkan kemenangan pasukan Kediri-Panjalu Jayati di bawah Sri Mapanji Jayabhaya sewaktu menghancurkan kekuatan musuhnya, raja Hemabhupati di Ngantang. Makam ini menurut cerita berkaitan dengan sejumlah makam purbakala di pantai Utara Jawa yang diyakini sebagai makam tokoh Syaikh Subakir.
Membicarakan Ngantang sendiri, tak banyak orang yang tahu bahwa daerah ini menyimpan sejarah yang panjang. Catatan sejarah pertama mengenai daerah ini adalah prasasti Hantang yang konon menjadi asal mula kata “Ngantang”. Prasasti ini merupakan prasasti dari zaman kerajaan Kediri yang berangka tahun 1057 Saka (1135 M). Prasasti Hantang dibuat oleh Raja Jayabhaya (Raja Kediri). Raja Jayabhaya berterimakasih kepada penduduk daerah yang kini disebut Ngantang karena telah berjasa kepada kerajaan Kediri. Penduduk di daerah itu telah membantu usaha kerajaan Kediri untuk mengalahkan kerajaan Jenggala. Seperti yang diketahui, setelah meninggalnya Airlangga, kerajaan Kahuripan dipecah menjadi dua, yakni “Panjalu (Kediri) dan Jenggala”. Dua kerajaan ini saling berebut kekuasaan terutama di daerah sekitar aliran Sungai Brantas, Jawa Timur.
Perseteruan dua kerajaan ini berakhir setelah kerajaan Kediri mampu mengalahkan Kerajaan Jenggala. Salah satu faktor kemenangan Kerajaan Kediri adalah bantuan dari masyarakat Ngantang. Saat perang berlangsung, masyarakat Ngantang begitu setia terhadap Kediri. Sebagai rasa terimakasih, Raja Jayabhaya memberikan prasasti Hantang. Di dalam prasasti itu terdapat tulisan “Narasinga dan Panjalu Jayati (Panjalu Menang)”. Selain itu, Ngantang juga menjadi daerah istimewa kerajaan Kediri. Kemenangan Kediri atas Jenggala ini juga disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Kurawa dalam Kisah Bharatayudha yang digubah oleh Mpu Sedah dan Mpu Panuluh tahun 1157 M.
ARTEFAK DI PUNDEN LUMPANG KENTHENG

Punden Lumpang Kentheng. Tepatnya di dusun Pakan desa Purworejo kecamatan Ngantang kabupaten Malang. Artefak berbentuk lumpang dan alu yang berada di Kompleks punden kecamatan Ngantang Kabupaten Malang memiliki nama Lingga dan Yoni. Nama Lingga melekat pada alu. Yoni merupakan nama dari lumpang, keduanya terbuat dari batu. Abdul Aziz Ketua LESBUMI, mengatakan Lingga dan Yoni yang berada di Kompleks Punden Lumpang Kentheng bekas alat penumbuk padi pada era awal Islam masuk di Ngantang. “Awal masuknya Islam, Lingga dan Yoni digunakan sebagai penumbuk padi. Lingga dan Yoni ini sering dikisahkan di kisah pewayangan yang tak lepas dari kisah-kisah masa Hindu,” tutur Abdul Aziz, Sabtu (6/09/2025). Artefak Lingga juga bisa diartikan sebagai simbol kejantanan pria. Artefak Lingga juga bisa diartikan sebagai simbol kejantanan pria. Foto/ dokumentasi: LESBUMI PCNU kabupaten Malang. Abdul Aziz menjelaskan, Lingga merupakan gambaran dari laki-laki karena bentuknya yang mirip dengan alat kelamin pria. Lingga juga bisa diartikan sebagai simbol kejantanan pria. Sedangkan Yoni, sambung Abdul Aziz, menggambarkan perempuan karena bentuknya mirip dengan alat kelamin perempuan. Diartikan juga sebaga simbol kesuburan perempuan. “Dalam bahasa Sansekerta nama purusa lingga diartikan sebagai alat kelamin pria.
Sedangkan yoni diartikan sebagai kekuatan gaib yang memiliki daya tarik luar biasa. Simbol Lingga dan Yoni jelas dipengaruhi simbol-simbol Hindu. Karena itu simbol Lingga dan Yoni selalu berada di tengah komplek bangunan yang dipengaruhi Hindu. Lebih lanjut Abdul Aziz menjelaskan, pada masa Hindu, Lingga dianggap sebagai simbol Dewa Siwa. Ia mengatakan simbol Lingga dan Yoni yang terbuat dari batu itu merupakan petunjuk bahwa Lingga dan Yoni sempat digunakan untuk keperluan ritual. “Benda itu memiliki kemungkinan dijadikan sebagai sarana pemujaan bagi lingkungan pada zaman Hindu, sebelum Islam masuk. Namun sangat disayangkan pada Punden Lumpang Kentheng yang tersisa hanya Lingganya saja, sementara Yoni-nya dari hasil informasi kami gali dari masyarakat setempat sudah hilang sejak lama.
Tegas! Abdul Aziz, di era moderen saat ini simbul dari Lingga dan Yoni masih sering kita jumpai, seperti dibuat untuk simbul tugu pada perbatasan antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain, perbatasan kota dan kabupaten misalkan. Seperti tugu Monas di Jakarta secara filosofis ia mengambarkan Lingga dan Yoni yang secara filosifis mengambarkan kesuburan umat manusia. Tugu-tugu perjuangan meskipun itu mengambarkan pluru atau bom namun secara filosifis mengambarkan Lingga dan Yoni kesuburan umat manusia. Jika kita simpulkan umat manusia ini harus terus hidup dan berkembang biak, dalam pandangan kajian Islam umat manusia harus terus hidup dan mengembangkan sumber daya manusianya dalam rangka meneruskan risalah ajaran Rasulillah Saw, yakni; manusia adalah “khalifatul ardhi” di muka bumi, ia adalah pemilik saham, pemilik sumber daya alam, maka sebagai pemilik saham, pemilik sumber daya alam, ia harus di bekali ilmu pengetahuan agar dapat menghantarkannya kepada kejayaan dan kemakmuran umat manusia, bukan malah sebaliknya! Merusak alam, merusak lingkungan sebagai warisan leluhur secara turun temurun yang sejatinya menjadi misi mulia untuk senantiasa di jaga, di rawat untuk sumber kelangsungan hidup umat manusia.
“BATU PRANATA MANGSA” DI AREA MAKBAROH KI AGUNG JOYO SUNTONO

Perjalanan kami berikutnya ke area makbaroh “ki Agung Joyo Suntono”, tepatnya di desa Tulungrejo Gagar kecamatan Ngantang kabupaten Malang, pada Sabtu, 6 September 2025. Jam; 10:21 Wib. Setelah poresesi “tawasulan, tahlil dan umbul dungo” kami haturkan. Ada sesuatu yang menarik pada pojok makbaroh ini, yakni; sekilas tanpa dari kejauhan seperti batu dakon yang umumnya di buat permainan anak-anak. Namun bukan, ini adalah “Batu Pranata Mangsa” atau dalam bahasa keseharian atau umumnya masyarakat saat itu menyebutnya “matematika Jawa atau hitung-hitungan Jawa”. Dari beberapa catatan yang kami gali atau litelatur yang kami dapat, maupun tradisi masyarakat saat itu, menyebut pranata mangsa pada saat ini sudah mengalami beberapa pergeseran akibat perubahan iklim dan kemajuan teknologi. Meski demikian penanggalan ini masih bisa digunakan sebagai acuan dalam memahami teknologi prakiraan cuaca yang semakin maju. Dikutip dari buku “Pranata Mangsa karya Sindhunata”, ada 12 mangsa atau musim yang dikenal dalam pranata mangsa. Seperti sistem penanggalan lainnya, tiap mangsa memiliki bintang yang merupakan pedoman berawal atau berakhirnya suatu mangsa. Setiap mangsa juga memiliki watak dan berpengaruh pada pengolahan tanaman. Meski terkesan mistis “wingit”, hal tersebut merupakan hasil dari pengalaman nyata dan pengamatan rasional para petani di masa lampau atau memiliki “daya titen” yang luar biasa.
Mangsa Kasa adalah dimana masa atau musim berumur 41 hari, dimulai pada 22 Juni hingga 1 Agustus. Biasanya, para petani pada musim ini mulai membakar sisa batang padi di sawah dan mulai bertanam palawija. Mangsa Kasa ini memiliki watak “sesotya murca ing embanan” atau permata yang terlepas dari cincin pengikatnya. Watak ini menggambarkan kondisi daun yang berguguran. Biasanya musim ini ditandai dengan belalang yang mulai membuat lubang dan bertelur.
Mangsa Karo ini berumur 23 hari, yaitu mulai 2-24 Agustus. “Sindhunata” menuliskan di musim ini manusia mulai resah karena alam yang kering dan panas.
Musim ini memiliki watak bantala rengka yang berarti tanah retak dan berbongkah. Banyak pula yang menyebutnya sebagai musim paceklik. Di musim ini biasanya palawija yang ditanam oleh petani mulai tumbuh. Meski panas, pohon randu dan mangga mulai bersemi.
Mangsa Katelu umumnya berumur 24 hari, mulai 25 Agustus hingga 17 September. Di musim ini paceklik semakin memuncak. Musim ini memiliki “watak suta manut ing bapa” yang berarti anak yang mematuhi ayahnya. Watak ini menggambarkan palawija yang mulai tumbuh mengikuti turusnya. Sebagian tanaman palawija sudah bisa dipanen pada musim ini.
Mangsa Kapat ini memiliki umur 25 hari, mulai 18 September hingga 12 Oktober. Kesabaran para petani diuji pada musim ini. Di Mangsa Kapat ini digambarkan sebagai “waspa kumembeng jroning kalbu” atau air mata yang tersimpan di hati. Meski demikian, musim ini merupakan akhir dari kemarau. Para petani biasanya mulai menyiapkan bibit tanaman padi. Masyarakat menandai masuknya Mangsa Kapat dengan banyaknya burung pipit yang membuat sarang dan bertelur. Pohon randu juga mulai berbuah.
Mangsa Kalima Mangsa Kalima berumur 27 hari, mulai 13 Oktober hingga 8 November. Di musim ini hujan akan mulai turun. Watak dari Mangsa Kalima ini adalah pancuran mas sumawur ing jagad atau hujan yang tersebar di bumi. Para petani biasanya mulai mengolah sawah dan membuat irigasi. Mereka juga mulai menyebar benih padi gaga atau pagi lahan kering. Di musim ini pohon asam mulai tumbuh daun muda. Ular dan ulat juga mulai keluar.
Mangsa Kanem umur Mangsa Kanem ini cukup panjang yaitu 43 hari, mulai 9 November-21 Desember. Curah hujan semakin tinggi. Watak dari Mangsa Kanem ini digambarkan sebagai rasa mulya kasucen atau rasa mulai dari kesucian. Watak ini menggambarkan musim yang indah karena banyaknya berkah dari alam. Meski harus bekerja keras, para petani menggarap sawahnya dengan bergembira. Musim ini biasanya ditandai dengan banyaknya burung belibis mencari makan di kolam. Lipas juga banyak ditemukan di parit.
Mangsa Kapitu memiliki umur 43 hari, mulai 22 Desember hingga 3 Februari. Mangsa ini masih menjadi bagian dari musim penghujan. Watak dari mangsa ini digambarkan sebagai wisa kentar ing maruta atau racun yang terbang tertiup angin. Pada mangsa ini banyak orang tertular sakit. Bencana berupa banjir dan angin ribut juga sering muncul pada musim tersebut.
Mangsa Kawolu relatif berumur pendek, dari tanggal 3 Februari hingga 28 atau 29 Februari. Musim ini digambarkan sebagai “anjrah jroning kayun” atau tersebar merata di dalam hati. Para petani bergembira karena tanaman padi mulai berbunga. Mangsa Kawolu ini juga memiliki tanda alam berupa banyaknya kucing yang kawin.
Mangsa Kasanga memiliki umur 25 hari, dari 1-25 Maret. Para petani bergembira karena padinya sudah siap untuk dipanen. Musim ini memiliki wedharing wacana mulya atau tersiarnya kabar gembira. Pada masa ini sebagian padi sudah mulai berbunga, sebagian lagi sudah berbuah. Tanda alam dari mangsa ini adalah munculnya serangga seperti tonggeret, jangkrik dan gangsir yang terus berbunyi.
Mangsa Kasapuluh adapun memiliki umur 24 hari, mulai 26 Maret hingga 18 April. Musim ini juga menandai berakhirnya musim penghujan. Musim ini memiliki “watak gedhong mineb njroning kalbu” atau buah hati di dalam hati. Para petani sibuk menjaga padinya dari serangan burung pipit. Selain itu, musim ini juga ditandai dengan banyaknya hewan yang hamil dan burung yang bertelur.
Mangsa Dhesta memiliki umur 23 hari, mulai 19 April hingga 11 Mei. Musim kemarau sudah semakin dekat. Musim ini digambarkan sebagai “sesotya sinarawedi” atau permata hati penuh kasih sayang. Di musim ini burung-burung menyuapi anaknya yang baru menetas. Adapun para petani akan sibuk memanen padinya pada musim ini.
Mangsa Sada kurang lebih berumur 41 hari, mulai 12 Mei hingga 21 Juni. Musim kemarau dimulai pada mangsa ini. Musim ini digambarkan memiliki “watak tirta” sah saking sasana atau air yang menghilang dari tempatnya. Hujan tak lagi turun di musim ini. Cuaca yang panas dimanfaatkan oleh para petani untuk menjemur gabah untuk kemudian disimpan dalam lumbung. Musim ini juga digunakan oleh petani untuk mulai bertanam palawija.
Nah, setelah melihat secara utuh terkait fungsi dan penggunaan Batu Pranata Mangsa dapat kita simpulkan merupakan penanggalan berbasis peredaran semu matahari. Pada zamannya, penanggalan ini bisa sangat diandalkan oleh para petani untuk mengatur jadwal bercocok tanam. Bahkan, penanggalan ini pernah menjadi salah satu bahan ajar pendidikan formal. Dalam artikel Pranata Mangsa dan Budaya Kearifan Lokal di Jurnal Budaya Nusantara, Supardiyono Sobirin menyebut pranata mangsa masuk dalam kurikulum di era Orde Lama. Hal tersebut terjadi sekitar tahun 1950-1960. Saat itu para siswa Sekolah Rakyat di daerah Solo, Yogyakarta dan sekitarnya harus mempelajari pranata mangsa. Sistem penanggalan ini sebenarnya sudah digunakan oleh para petani di Jawa sejak masa lampau. Namun, pada akhirnya penanggalan pranata mangsa ini dibakukan di era Paku Buwono VII sekitar tahun 1855.
“BATU PRANATA MANGSA” DI AREA PUNDEN LUMPANG KENTHENG

Foto/ dokumaentasi ini pada Sabtu: 6 September 2025. Jam; 13:15 Wib. Tampak Batu Pranata Mangsa lebih detail dan lebih jelas posisinya, bisa juga faktor alam karena posisinya di luar jadi tampak lebih jelas dan bersih. Seperti uraian di atas fungsi dan kegunaan Batu Pranata Mangsa ini adalah sama. Batu Pranata Mangsa yang kedua kami melihatnya di Punden Lumpang Kentheng yang juga satu area dengan makbaroh seorang ulama sepuh “Mbah Wali Ageng”, setelah umbul doa dan tahlil kami haturkan, kami mencoba mendokumentasi beberapa artefak yang masih ada dan utuh di Punden Lumpang Kentheng ini. Selain batu Pranata Mangsa, disini juga terdapat batu Lumpang dan batu Giling beras. Sementara batu Lumpang dulu biasanya di gunakan oleh masyarakat setempat dibuat untuk menumbuk padi, jagung, kopi dan lainnya. Sementara batu Giling beras biasanya di gunakan untuk membuat tepung beras, setelah beras melalui proses perendaman. Ujar, Abdul Aziz. Kami sangat bersyukur di punden ini masih terawat dan terjaga serta ada kesadaran dari warga setempat untuk nguri-nguri punden Lumpang Kentheng.

Liputan langsung LESBUMI PCNU Kabupaten Malang di kecamatan Ngantang
Oleh: Abdul Aziz Syafi’i (ketua LESBUMI)