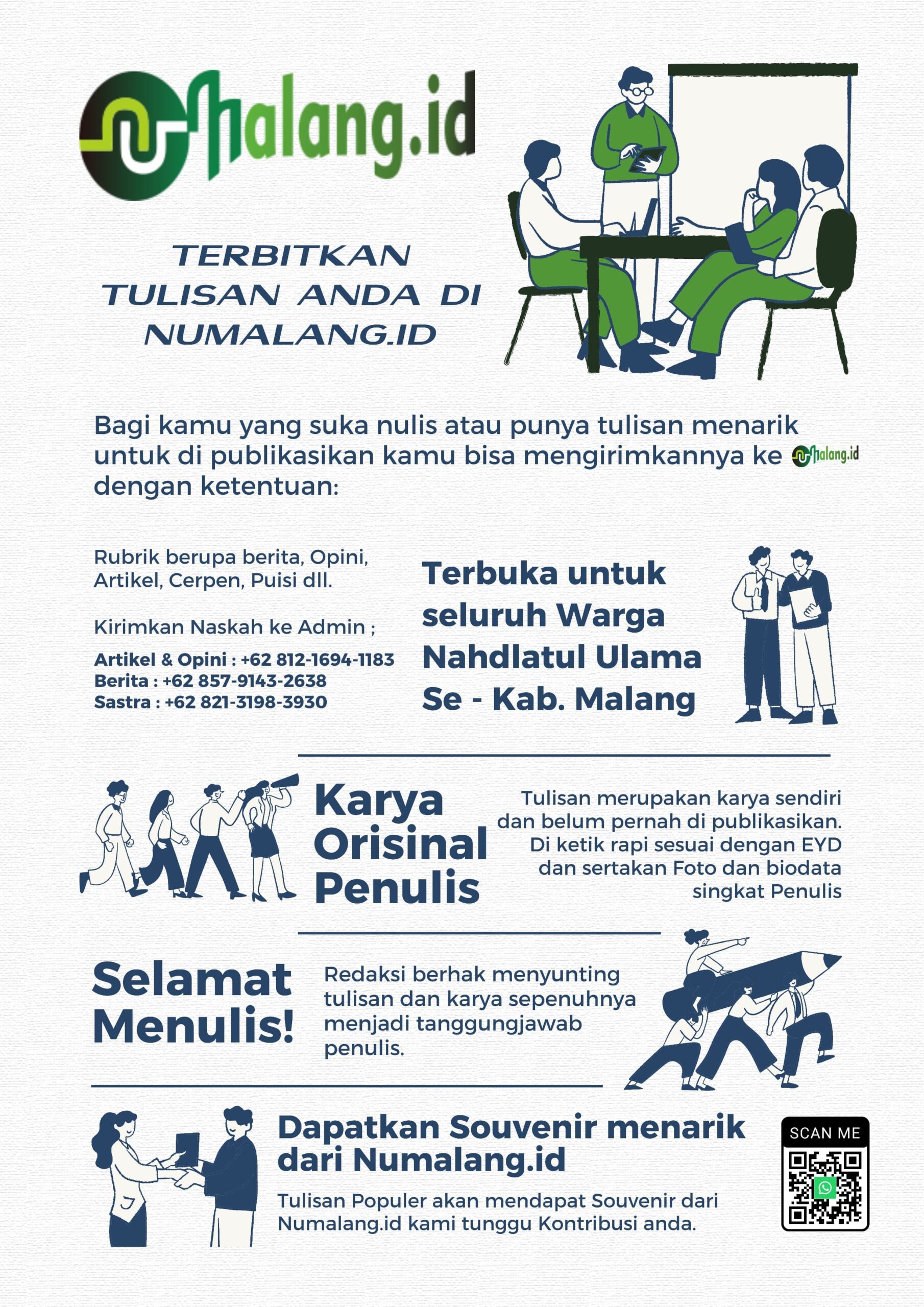NUMALANG.ID.-
Sobo Deso NGAJI SEWELASAN: “Nyadran dan Selamatan Karo Masyarakat Adat Suku Tengger, Mapak Keberkahan”
Kamis Kliwon; 21 Agustus 2025, Tempat; Dusun Tosari Desa Duwet Kec. Tumpang Kab. Malang, Jam; 19:26 WIB
Iftitah?
Nyadran adalah suatu“Tradisi yang mengandung maksud penghormatan kepada leluhur sekaligus ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt”.
Nyadran atau Sadranan adalah tradisi yang dilakukan orang Jawa pada bulan Sya’ban dalam kalender Hijriyah atau Ruwah kalender Jawa yakni, ungkapan rasa syukur yang dilakukan secara kolektif dengan ziarah ke makam leluhur yang ada di kelurahan atau desa. Nyadran di maksudkan sebagai sarana atau “wasilah” dalam bahasa Pesantren untuk mendoakan leluhur yang telah meninggal. Menjadi sarana pengingat bahwa semua manusia akan mengalami kematian serta nguri-nguri budaya gotong royong dalam masyarakat serta menjaga harmonisasi bermasyarakat, kemudian pada kegiatan ini di tutup dengan “kembul bujono” atau kendurenan yakni makan bersama.
Dari aspek etimologis, nyadran diambil dari berbagai bahasa. Pertama, bahasa Indonesia, dalam KBBI (2010). Sadran-menyadran diartikan “mengunjungi makam” pada bulan Ruwah untuk memberikan doa kepada leluhur, seperti; (tokoh sepuh dan atau bedah krawang desa, ayah, ibu dan lainnya) dengan membawa bunga atau sesajian. Kedua, bahasa Sanskerta, sraddha artinya keyakinan. Ketiga, nyadran dalam bahasa Jawa berasal dari kata sadran yang artinya Ruwah Sya’ban lantaran dilakukan sebelum Ramadhan. Keempat, nyadran diambil dari bahasa Arab, shadrun yang berarti dada. Khamim (2018) berpendapat menjelang Ramadhan, masyarakat harus ndada (introspeksi diri), menyucikan diri dari aspek lahir dan batin. Di berbagai daerah, nyadran memiliki idiom dan praktik beda.
Di Jawa Timur, sebagian orang melakukan nyadran, seperti yang dilakukan masyarakat “muslim adat suku Tengger” yang ada di daerah Tosari-Duwet kecamatan Tumpang kabupaten Malang, kegiatan ini sudah turun temurun, masyarakat setempat melakukan kegiatan nyadran di makam sesepuh atau tokoh bedah krawang desa yakni, di “makam punden mbah Kerto dan mbah Sari”, tepatnya di Rt 30 Rw 07 dusun Tosari desa Duwet adapun rangkaian acaranya di mulai dengan “ngujub, ngujobno” atau dalam bahasa Pesantren menyebutnya menyampaikan mukodimah maksud dan tujuan, secara umum ngujub adalah menghaturkan maksud dan tujuan dari acara nyadran dan selamatan Karo yang berisi doa-doa, harapan, cita-cita luhur serta diberi kemakmuran dan di jauhkan dari bala’ dilakukan oleh tokoh sepuh setempat atau kepala adat setempat yakni mbah dukun, kemudian di tutup dengan doa secara Islam yang di pimpin kyai atau ulama sepuh setempat, artinya kegiatan tersebut masih kental dalam konteks Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan ciri khas seperti tawasulan, istighosah serta bacaan tahlil, di tutup dengan doa dan kemudian “kendurian tumpeng gede” atau kendurenan, makan bersama.
“PERHITUNGAN WAKTU DAN RUANG WAKTU”. Istilah Karo?
Suku Tengger membagi tahun menjadi 12 bulan yang berganti-ganti antara 30 dan 29 hari (jadi totalnya 354 hari) dan diberi nama sebagai berikut : 1. Kasa. 2. Karo. 3. Katiga. 4. Kapat. 5. Kalima. 6. Kanem. 7. Kapitu. 8. Kawolu. 9. Kasanga. 10. Kasepuluh. 11. Desta. 12. Kasada.
Nama 10 bulan pertama berasal dari bahasa Jawa, sedangkan 2 bulan terakhir berasal dari bahasa Sansekerta “Jyestha dan Asadha”. Pembagian yang sangat lama menjadi puluhan muncul dari cara primitif menghitung dengan 10 jari, analog dengan ini adalah pembagian minggu menjadi 5 hari atau lima malam (menghitung 5 jari), demikian juga pembagian hari menjadi 5 ruang waktu. John Crawfurd-lah yang dalam History of the Indian Archipelago, pertama kali dengan jelas menunjuk pada hitungan jari ini dalam perhitungan Jawa kuno. Sepuluh mangsa muson kuno diatur untuk pertanian menurut konstelasi tertentu, yaitu sabuk dan pedang Orion dan Pleiades, yang masih dikenal di kalangan orang Jawa sebagai “lintang luku” dan “lintang wuluh”.
Dalam gambar kelompok Orion terlihat bajak (waluku), digantung dengan kerbau. Baik pada malam hari, atau pagi-pagi sekali, saat senja, petani memperkirakan ketinggian rasi bintang ini di atas cakrawala, dan musim hujan ditentukan dari ketinggian ini (1).
1) Lihat J.A.C. Oudeman: Pemberitahuan tentang rasi bintang, dll. di Laporan dan Pengumuman Koninkl. Akademi Ilmu Pengetahuan, seri ke-2, Bagian 16, 1881. Kalender mangsa tertua, yang menunjukkan bahwa pada 10 muson ditambahkan bulan ke-11 dan ke-12 masing-masing atas nama “Hapit lemah” dan “Hapit kayu”, dibuat oleh Dr. Brandes menerjemahkan dalam esainya: Nama bulan Hapit (Tijdschr. voor Ind. Taal, Land-en Volkenk. vol XLI, 1899). Dua bulan Hapit lemah dan Hapit kayu ditarik kembali atau diintervensi (yaitu hapit) sebagai waktu mati setelah semua pekerjaan ladang dilakukan, jadi ketika padi telah dipanen dan ditumbuk (2).
2) Nama bulan Hapit lemah dan Hapit kayu masih digunakan oleh suku Badui (lihat karya: The Badoej’s of Dr. J. Jacobs dan JJ Meyer dan J. Hageman’s Manual to the knowledge of history, etc. of Java) .
Dr. Brandes telah menunjukkan bahwa kedua nama ini sudah digunakan oleh umat Hindu pada abad ke-11, dan pasti sudah ada beberapa kebingungan atau pencampuran nama-nama ini dengan Jyestha dan Asadha.
Di masa lalu, demi kemudahan, para petani, bahkan sekarang pun kurang lebih demikian dalam melakukan kerja lapangan-menurut fenomena yang diamati pada atau pada tumbuhan dan hewan, dan kemudian panjang bayang-bayang manusia pada titik puncak matahari, ditambahkan ke penunjukan musim.
Jadi muson pertama Kasa (21 Juni-31 Juli), ketika bayangan manusia terletak empat kaki ke selatan dan ikan air tawar “iwak betik” mendapat satu lubang di kepalanya, adalah waktu untuk menanam tanaman kedua. Di Karo (1-23 Agustus), ketika bayangan manusia berada 2 kaki ke selatan, iwak betik memiliki 2 lubang di kepalanya, inilah saatnya untuk merawat tanaman kedua.
Nyadran di tempat lain seperti di Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Surabaya, Gresik dan lainnya. Meski berbeda, di Jawa Barat juga sama, namun secara umum berbeda karena tidak ada tradisi makan bersama di kuburan. Mereka hanya datang ke makam, tabur bunga, mendoakan dengan membaca surat yasin dan tahlil, lalu pulang. Di Semarang, Demak, Kendal, para warga datang ke kuburan mendoakan leluhur-kedua orang tua. Ada yang membawa makanan dan ada yang tidak. Di Grobogan, Pati, dan sekitarnya, selain berkunjung ke kuburan, nyadran disebut megengan dipraktikkan lewat tasyakuran bersama di langgar-masjid sebelum Ramadhan. Di Blora, nyadran dipraktikkan dengan besik kubur (membersihkan kuburan) dari kotoran. Di Temanggung, Magelang, Salatiga, Solo, Yogyakarta, nyadran dilakukan di tiap dusun atau kampung dengan berziarah ke kuburan. Mereka melakukan tahlil, doa bersama, meminta ampunan dan keseimbangan dengan alam. Dalam konteks sosial, nyadran menjadi rangkaian budaya mulai dari pembersihan makam leluhur dan tabur bunga dan mendoakan mereka. Di sejumlah tempat, nyadran berkembang menjadi ‘paket wisata’ budaya dan religi karena hanya ada di Nusantara ini.
Umat Islam di Jawa Tengah bahkan di Nusantara melakukan nyadran menjelang Ramadhan, bahkan di sebagian daerah sampai menjelang Idul Fitri. Secara umum, nyadran memang dilakukan menjelang Ramadhan. Tapi di sebagian daerah, justru nyadran dilakukan menjelang Idul Fitri. Tradisi ini memiliki nilai “adhiluhung”. Mulai dari religiusitas, kearifan lokal, dan nasionalisme. Nyadran juga wujud relasi antara manusia, leluhur, alam, dan Allah Swt. Di tengah gempuran paham konservatif dan radikal saat ini, masyarakat harus melestarikan kearifan lokal dan nasionalisme. Tujuannya, membentengi berkembangnya ideologi terorisme dan transnasional yang mengusik NKRI. Adanya faham takfiri (mengafirkan), tabdi’ (membidahkan), tasyri’ (mensyirikkan) merupakan bentuk pemahaman Islam konservatif, kaku-jumud, dan doktriner. Puncaknya, paham ini berbentuk tindakan keji berupa merusak sampai pengeboman. Padahal, teror bukan jihad dan ajaran Islam. Agama tak sekadar urusan doktrin ideologis. Agama harus dipahami sebagai “realitas sosial”. Maka perbuatan sehari-hari tak boleh kaku karena harus sesuai konteks, lingkungan, budaya dan kebutuhan zaman. Orang berpaham kaku dan konservatif cenderung inferior dengan bangsanya sendiri karena tak memiliki spirit nasionalisme. Mereka berpaham yang lain salah kecuali aku. Seolah-seolah surga sudah dikapling dan yang tak sepaham tempatnya di neraka. Jika demikian, wajar jika ada aksi terorisme. Cara dakwah mereka pun memukul bukan merangkul. Doktrin jihad harusnya memajukan justeru menjadi jahat. Dari sini, tradisi nyadran menjadi bagian menggerakkan dan menguatkan nasionalisme. Jika masyarakat semuanya nasionalis, tak mungkin ada pengeboman karena mereka cinta tanah air. Merawat Kearifan Lokal Idiom nyadran sudah menasional. Pemeluk Islam di Nusantara memang unik. Hampir tiap tradisinya berkaitan dengan Allah Swt, alam, dan manusia. Contohkan saja nyadran, krayahan, kondangan, bancakan, manganan, megengan, dan lainnya. Selain ada makan-makan, sedekah, mereka melakukan doa-doa dan membaca ayat Al-Qur’an. Tradisi ini harus dijaga sebagai khazanah budaya dan identitas bangsa. Nyadran membangun masyarakat menjadi seimbang dan sesuai ruh Islam.
Melalui nyadran, mereka mampu menciptakan kemesraan ruhani antara manusia dengan sesamanya, dengan Allah Swt dan alam “hablum minalalam”. Nyadran tak hanya urusan religi, namun erat kaitannya dengan budaya, nasionalisme, bahkan pariwisata. Pemahaman nyadran harus komprehensif dan berbasis masa depan. Lewat nyadran bangsa ini menjadi besar karena memegang teguh identitas, kearifan lokal, dan nasionalisme. Nasionalisme Kuatnya nasionalisme menjadi syarat terwujudnya bangsa besar. Nasionalisme dan religiusitas satu kesatuan. Kita memiliki imperium ideologi bangsa berupa Pancasila. Ditambah pilar Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Semua itu sudah final karena dulu sebelum perumusan Pancasila, KH. Hasyim Asyari pendiri NU melakukan puasa berbulan-bulan meminta petunjuk pada Allah Swt. Hasilnya, ketika Bung Karno bertanya pada Mbah Hasyim, nasionalisme yang ditambahi dengan niat ibadah dan bacaan basmalah sudah islami. Nasionalisme dengan doktrin hubbul wathan minal iman (cinta tanah air sebagian dari iman) harus digerakkan dengan sikap superior. Mulai dari nasionalisme budaya, kewarganegaraan, etnik, romantik, sampai nasionalisme religius-agama. Jika ini dipegang kuat, maka tak mungkin ada terorisme. Dalam nyadran, ada beberapa landasan menguatkan nasionalisme dan spirit religiusitas. Penguatan nasionalisme ini bisa dilakukan sinergi dengan lembaga pendidikan sejak dini berkolaborasi dengan LP Maarif NU misalnya sampai perguruan tinggi (PTNU) dan komunitas budaya yang bermuara pada karakter toleran dan humanis. Spirit transnasional yang mencetak generasi antitradisi dan antinasionalisme harus diputus lewat pembudayaan dan literasi toleransi. Keempat, nyadran menjadi cara merawat tradisi agama-budaya dan nasionalisme. Kuatnya tradisi lokal suatu bangsa, maka nasionalisme makin kuat. Jika sudah kuat, tak mungkin masyarakat meneror. Nasionalisme harus dikuatkan untuk memutus embrio terorisme.
Akhirnya; LESBUMI sobo deso Ngaji Sewelasan sebagai wasilah, sebagai media silaturrahmi serta kaderisasi non struktural bagi kader-kader LESBUMI ataupun embrio-embrio LESBUMI pada akar rumput. Semoga senantiasa membawa keberkahan dan kemanfaatan. Amin.
Penulis: Abdul Aziz Syafi’i (Ketua LESBUMI PCNU Kabupaten Malang)
Disari dari catatan ngaji bersama alm. KNg. H. Agus Sunyoto di pesantren Global Tarbiyatul Arifin.